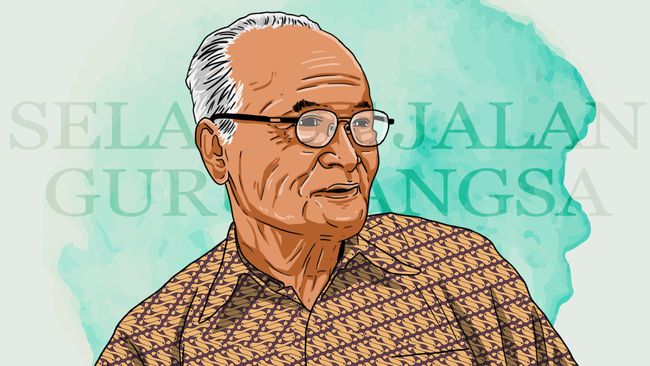 |
| ilustrasi: detik.com |
Bagi anak belia (gen Z) yang baru lahir kemarin sore seperti saya, kiranya sangat sulit mengenal dan menjangkau para tokoh yang besar di Muhammadiyah secara langsung. Meski, saya tumbuh cukup lama di lingkungan Muhammadiyah, lebih tepatnya ketika menjadi siswa SMP dan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, tetap saja itu tidak membuat saya, siswa biasa ini bertemu langsung dengan para tokoh Muhammadiyah.
Butuh pergaulan yang luas, dan
karier organisasi otonom yang bagus, agar memiliki jejaring luas sampai bisa
bertemu para tokoh besar Muhammadiyah itu. Sedangkan saya, hanya pernah dua
tahun duduk sebagai pengurus ranting IPM di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, dan
setahun duduk sebagai pengurus IMM level komisariat di kampus, itu pun hanya
sebagai pupuk bawang.
Bukan berarti tokoh elit
Muhammadiyah susah dijangkau, kebanyakan dari mereka, seperti Buya Syafii,
berdasar kesaksian teman-teman, adalah
sosok yang ramah dan mudah ditemui. Ini lebih karena belum ada kesempatan yang
pas saja. Apalagi Buya, berdomisili di Yogyakarta, saya berdomisili di
Boyolali.
Meski terasa jauh secara geografis dan belum pernah sama sekali bertemu. Saya merasa memiliki, merasa mengenal, dan merasa dekat. Sebabnya satu hal, Buya Syafii adalah penulis yang paling konsisten dan pembaca yang tangguh.
Oleh karenanya, meski fisik tidak
pernah bersentuhan, melalui pemikiran dan tulisan beliau di media, juga melalui
buku-bukunya, saya mendapat kesempatan yang sama—bahkan lebih intim—untuk
bertemu dan bersentuhan di alam pikiran. Itu karena tulisan-tulisan beliau
sampai kepada saya. Dua hal inilah menjadi kekuatan Buya Syafii, konsistensi
menulis dan ketangguhan membaca, inilah juga yang berusaha saya teladani dari
orang tua bernama Ahmad Syafii Maarif itu.
Menulis Sejak Muda
Buya Syafii sudah menulis sejak ia duduk di bangku sekolah, ketika ia masih menjadi siswa Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, sekolah setingkat SMA ini, didirikan oleh Ahmad Dahlan sebagai sekolah kader.
Dalam autobiografinya, Titik-titik Kisar di Perjalananku (2009) di sekolah inilah ia mulai
belajar menulis. Buya Syafii turut menjadi redaktur majalah Sinar yang diterbitkan dan dimotori oleh
para pelajar Mu’alimin. Posisinya sebagi redaktur majalah, tentu turut mengasah
kepekaan dan ketajamannya menulis, sampai membentuk gaya kepenulisannya kalak.
Menariknya, Buya Syafii kala itu,
sekitar tahun 1954, sudah menulis tentang politik nasional. Buya umumnya
menulis tentang wacana politik yang pro-Masyumi dan otomatis berlawan dengan
wacana politik PKI. Meski butuh waktu sekitar tiga tahun pada 1957, tulisan Buya,
yang sekali lagi, kala itu masih duduk di Mu’alimin dimuat di majalah Hikmah, satu majalah resmi milik
Masyumi. Buya mengaku pada tahun-tahun itu mengidolakan partai Masyumi, oleh
karenanya ia sangat gembira ketika tulisannya muncul di majalah garapan Masyumi
itu.
Entah dari mana gairah menulis
yang begitu besar itu datang, menurut pengakuan buya Syaifii, ibu dan bapaknya
bukan pengarang yang membuahkan buku, “ayahku paling-paling terlatih menulis
surat biasa atau catatan untuk kepentingan dagangnya. Ibuku sendiri mungkin
belum pernah menulis” begitu tulis Buya (hl. 110).
Justru ini menegaskan bahwa
urusan menulis karya bukan sesuatu yang diturunkan begitu saja dari orang tua,
melainkan dari tradisi diskusi dan membaca buku yang tekun dalam jangka yang
lama. Dan saya rasa, lingkungan Mu’alimin, sudah pasti memiliki tradisi
keilmuan semacam itu.
Pada masa-masa setelahnya, bekal
menulis Buya Sayafii ini turut menyambung hidupnya. Ia pernah menulis buku-buku
pelajaran agama untuk sekolah, seperti sejarah islam, masalah ibadah dan sub
pelajaran agama lain. Honoriumnya, Buya gunakan untuk tambahan kebutuhan
sehari-hari. Kiash buya ini seklagus mengajarkan, menulis sebagai penyambung
hidup itu bukan aib. Tidak hanya itu, ia juga menulis makalah untuk forum
internasional.
Sangking cintanya dengan menulis,
di kamar kerja Buya Syafii yang menurut pengakuannya berantakan dan sumpek,
dipenuhi banyak dokumen, buku-buku, dan majalah. Di kamar itulah Buya merenung,
membaca, dan menulis buah pikirnya. Ini adalah jalan sunyi, yang hampir setiap
tokoh besar melewati. Rela berlama-lama menyepi, menyelami kesepian, sendiri
bersama buku. Meski Buya sendiri bingung, “apa yang direnungkan, kadang-kadang
juga tidak jelas benar ujung-pangkalnya (hl. 79).
Jalan sunyi yang ditempuh Buya
itu, yang akhirnya menghantarkan karier intelektualnya sampai ke Amerika, untuk
lebih mempertajam keilmuan dan tradisinya menulis, juga membaca. Buya mendapat
kesempatan meneruskan belajar melalui program Ph.D di Universitas Chicago. Di
tahap inilah, pikiran yang khas mengenai Islam dan kemanusiaan Buya Sayafii
terbentuk.
Sampai Usia Senja, Tetap Menulis
Sampai menjelang hari terakhir, buya masih sering menulis, termasuk menulis di rubrik Resonansi Koran Harian Republika. Itu Buya lakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Menulis bagi buya mungkin sudah seperti bernafas.
Tulisan-tulisan yang ia hadirkan selalu menyegarkan, ia kerap menulis isu
kebangsaan juga isu sosial yang aktual. Tidak jarang buya juga menyinggung
buku, yang saya ingat buku seperti sastra, Robohnya
Surau Kami (1956) milik AA. Navis,
dan buku Ahmed Kuru berjudul Islam, Authoritarianism, and
Underdevelopment (2019) yang ia
sadur dan perkenalkan pertama kali ke pembaca Indonesia.
Konsistensi menulis Buya hampir
selalu seputar topik kebangsaan, kemanusiaan, dan keislaman. Pengalaman
hidupnya dan ketajaman pikirannya yang terasah melalui bacaan dan renungan,
membuat ia pada akhirnya meninggal sebagai sosok ‘guru bangsa’. Jika kita
menyimak perjalanan dan karier intelektualnya, istilah mewah dan muluk-muluk
seperti ‘guru bangsa’ agaknya tidak berlebihan jika disematkan kepadanya.
Hingga di usia senja, Buya Syafii
tetap saja menulis, tetap membaca, tetap berdiskusi, dan merenung. Ia terus
saja bergairah, “pada usia senja menjelang malam ini, aku tetap saja menulis
dan menulis. Mungkin baru (akan) berhenti setelah tanganku tidak bisa digerakkan
lagi karena sudah renta dan keriput,” begitu pengakuan Buya.
Meski nyatanya, ia tidak berhenti
karena sudah tua renta atau keriput di tangannya, malah ia tetap terus menulis
dan menulis bahkan sampai akhir hidupnya. Kita cukup beruntung, pemikir seperti
Buya, rajin sekali menulis, dengan begitu mudah untuk merenungi pikir-pikiran
yang ia tinggalkan, meski raganya sudah tidak membersamai.
Akhirnya saya yang pernah bercita-cita sekedar bertemu dan mendengar Buya Syafii dan gagal ini, hanya bisa meneladani sosok Buya Syafii sebagai pembaca yang tangguh, juga sebagai penulis yang konsisten.
Sudah ratusan mungkin ribuan artikel yang ia tulis,
sudah puluhan mungkin ratusan buku yang ia rampungkan, tinggal kita, terutama
saya, menyelami pikiran-pikiran Buya lewat tulisan. Agaknya dalam hal ini, saya
tidak perlu menyesal meski tidak pernah bertemu, toh saya masih bisa bertemu
dengan pikiran Buya Syafii lewat tulisan, kapanpun dan dimanapun.