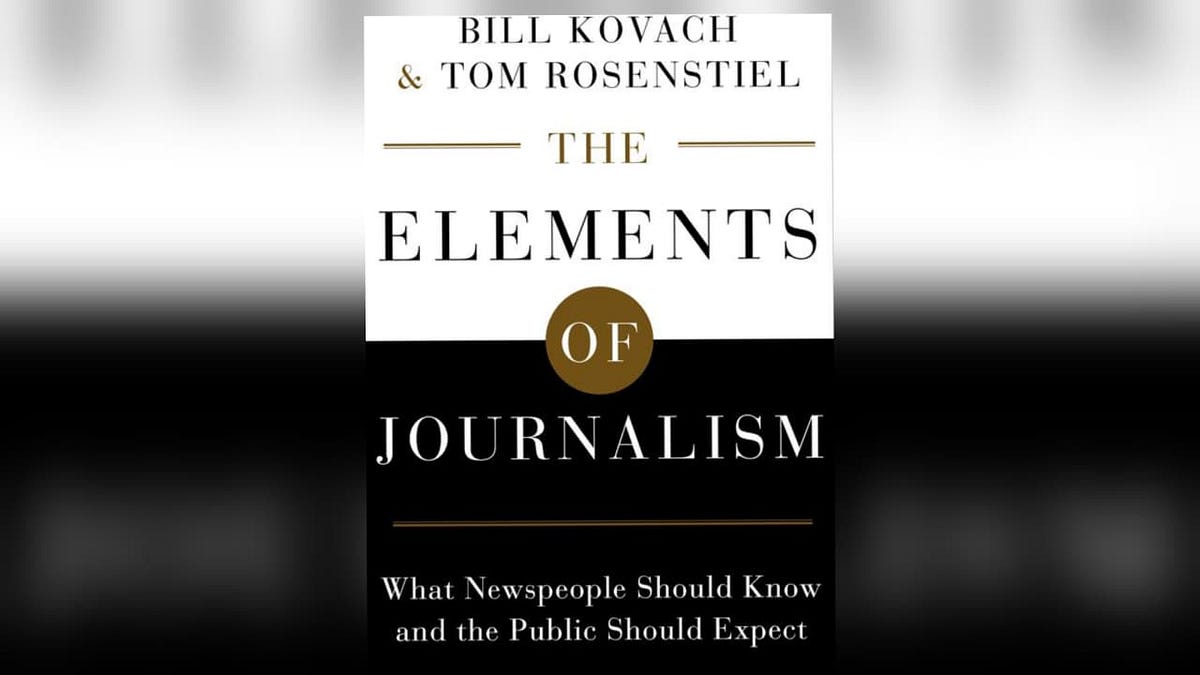Hari ini, dunia berubah menjadi serba digital. Perilaku orang mendapatkan informasi pun ikut berubah. Bagi yang pernah hidup di awal 2000-an, mungkin masih menemui perilaku orang-orang membaca koran untuk dapat asupan informasi.
Tapi hari ini, tidak lagi. Dengan telepon pintar, akses internet, dan sosial media, informasi itu sudah tidak perlu dicari, namun datang sendiri. Bahkan jumlahnya ratusan tiap detik, ribuan tiap menit, dan jutaan tiap jam. Sangat banyak. Kita boleh menyebutnya dengan “banjir informasi”.
Pertanyaannya sekarang adalah, di tengah banjir informasi ini, apa relevansinya kerja-kerja jurnalistik? Bukannya tugas seorang jurnalis adalah menyajikan informasi. Kalau informasi saja sudah bisa datang sendiri, buat apa jurnalis?
Pertanyaan ini harus direnungkan baik-baik. Sekaligus, kalau memang perlu, kita definisikan ulang tugas jurnalis hari ini. Sebab era sangat cepat berubah, dunia terasa bergerak sangat cepat sejak media sosial muncul.
Ditambah sekarang penggunaan kecerdasan buatan generatif atau generatif AI makin masif. Orang-orang kini sudah lumrah menggunakan Gemini, ChatGPT, dan lainnya. Generative AI bahkan bisa mengakses database Google seperti Gemini.
Dari semua perkembangan ini, sekali lagi saya akan tanya, masih relevan atau tidak profesi yang disebut jurnalis ini? Sebetulnya jawabannya sederhananya, “ya tentu masih.” Cuma saya akan sedikit berbelit-belit dan menawarkan argumentasi, kenapa kerja-kerja jurnalis masih dan akan terus relevan?
Saya meminjam istilah yang rumit ini dari buku Post-Truth (2018) karya Lee Mcintyre diterbitkan MTI Press. Lee menjelaskan kekacaun hari ini dengan istilah Post-Truth, atau jika diterjemahkan secara langsung, berarti Pasca-kebenaran.
Poin utama dari Post-Truth adalah kekacauan. Kekacauan yang saya maksud adalah betapa kaburnya kebenaran hari ini. Ini karena apa yang kita sebut di awal, yakni banjir Informasi. Informasi yang beredar di sosial sering kali bias, tidak mendasar, dan faktanya kadang belok.
Terlihat, misalnya pada 2019–2020 ketika pandemi Covid-19 semakin masif di Indonesia. Informasi di sosial media kadang lebih mengandung unsur konspirasi, dari pada fakta di lapangan. Di sisi lain, ilmuwan atau ahli di bidang virus masih sulit mendefinisikan Covid-19 secara akurat.
Itu membuat bingung masyarakat, akhirnya yang lebih dipercaya adalah informasi yang datang dari para influencer, bahwa Covid-19 itu diciptakan, ada chip di vaksinnya, dan seterusnya. Informasi yang begitu bias ini, membuat kebenaran menjadi kabur.
Di sini lah jurnlis dibutuhkan. Jurnalis punya tools yang tidak dimiliki oleh influencer, konten kreator, dan semacamnya. Jurnalis punya disiplin verifikasi yang tinggi. Ini juga tertulis di kode etik profesi.
Sehingga, ketika era sudah memasuki Post-Truth, tentu diperlukan orang-orang yang “menuntun” orang agar tidak bingung menemukan kebenaran, melalui informasi yang suda terverifikasi dan disampaikan kepada publik.
Profesi Jurnalis Melintasi Zaman
Lagian, profesi ini sudah sangat tua. Setidaknya, jurnalisme modern sudah ada sejak abad 17, setelah mesin cetak ditemukan. Ini teramat lama. Mari saya beri gambaran kenapa ini sangat lama. Revolusi industri pertama, dimulai sekitar abad ke-18, dimulai sekitar tahun 1760. Revolusi Industri 2.0: Pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Revolusi Industri 3.0: Sekitar tahun 1970-an, yaitu abad ke-20. Revolusi Industri 4.0: Awal abad ke-21.
Bisa dibayangkan, profesi jurnalis melewati empat revolusi industri selama ratusan tahun. Di semua zaman, kerja-kerja jurnalis tetap dibutuhkan. Maka, saya berani taruhan, profesi jurnalis tidak akan bisa digantikan mesin seperti AI.
Sebab, dari masa ke masa, kebutuhan masyarakat selalu sama. Masyarakat butuh kebenaran. Sedangkan kebenaran itu hanya bisa mereka dapatkan lewat informasi yang utuh, akurat, relevan, dan terverifikasi.
#Elemen Pertama: Kebenaran (Truth)
Dengan menjawab pertanyaan dasar itu, kita berhasil sampai pada elemen pertama yang ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku The Elements of Journalism (2001). Buku yang saya pegang untuk menulis artikel ini adalah edisi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Institut Studi Arus Informasi, cetakan kedua (2004).
Kovach meletakan kebenaran di urutan pertama, karena memang ini tugas pokok jurnalis. Jurnalis bisa saja salah, tapi ia tidak boleh bohong. Karena itu berarti mengingkari komitmen terhadap profesinya sendiri.
Namun kebenaran yang dimaksud seperti apa. Saya harus tekankan dulu perbedaan informasi dan kebenaran. Informasi bisa apa saja, termasuk gosip hingga hoaks. Tapi kebenaran di sini adalah penggambaran yang dekat dengan realitas.
Jurnalis punya kewajiban menyajikan informasi seakurat mungkin, agar masyarakat bisa menyusun kebenaran yang ia yakini, sehingga lebih dekat dengan realita. Tapi, tataran kebenaran yang dimaksud di sini, tidak sampai pada taraf filosofi.
Mengutip penjelasan Andreas Harsono dalam Agama Saya adalah Jurnalisme (2010) menyebut, dalam konteks jurnalisme, orang hanya butuh informasi lalu lintas agar bisa mengambil rute yang lancar. Orang butuh informasi harga, kurs mata uang, ramalan cuaca, hasil pertandingan bola dan seterusnya.
Inilah yang disuguhkan oleh jurnalis, sehingga masyarakat menafsirnya menjadi kebenaran dalam tataran yang lebih fungsional.
#Elemen Kedua: Untuk Siapa Jurnalisme Bekerja?
Tidak sulit menjawab pertanyaan ini, untuk siapa wartawan menyajikan informasi atau menunjukan ke arah yang benar? Jawabannya akan semudah tepuk tangan. Tentu kita semua tahu wartawan seharusnya bekerja untuk masyarakat. Itu artinya jurnalis harus selalu berpihak kepada kepentingan publik.
Publik bukan komoditi
Sayang tidak semudah itu. Media yang menaungi jurnalis adalah entitas bisnis. Demi kepentingan bisnis, sayangnya publik dianggap sebagai ceruk pasar dan komoditi. Jurnalis tidak jarang disuruh liputan untuk mendatangkan click atau view lebih banyak. Logikanya semakin banyak jumlah pembaca, makin banyak calon klien melirik untuk menaruh iklan.
Konglomerasi media, membuat jurnalis sibuk bekerja untuk pemilik perusahaan dan kepentingan bisnis, alih-alih untuk publik.
Hal semacam ini tidak lepas dari konglomerasi media. Jurnalis bukan pemilik media. Ia memang bekerja untuk publik, tapi satu sisi ada tekanan dari pemilik media untuk berpihak pada kepentingannya. Contoh paling gampang adalah pada masa Pilpres 2014. Media waktu itu terbelah menjadi dua kubu, ada yang memihak Jokowi dan ada yang memihak Prabowo.
Prinsipnya padahal media seharusnya tidak memihak, harus memihak publik. Namun karena ketua partai waktu itu juga pemilik media. Tidak heran, bisa dengan mudah menggunakan medianya untuk mengakomodasi kepentingan publik masing-masing.
Garis Api
Maka idealnya, seharusnya ada garis api untuk memastikan kepentingan publik terpenuhi. Agar jurnalis tetap bisa bekerja tanpa tekanan dan murni mencari fakta untuk publik. Gari api ini memisahkan antara kepentingan bisnis media dan kepentingan kerja-kerja jurnalis.
Contoh paling mudah adalah jika media A mendapatkan iklan dari Universitas B. Kemudian di kemudian hari, ada kasus dosen melecehkan mahasiswa. Jurnalis dari media A tetap harus memberitakan sesuai temuan di lapangan, dan tidak terpengaruh dengan iklan yang mengucur.
Lebih jauh, redaksi juga tidak boleh melarang jurnalis memberitakan mengenai kasus pelecehan itu hanya karena UMS sudah menjadi klien. Ini menjadi pertarungan “abadi” di meja redaksi dan bisnis.
#Elemen Ketiga: Verifikasi
Verifikasi menjadi kata kunci ketika membicarakan jurnalisme. Makanya, sejak awal kata ini terus disebut. Sebab verifikasi adalah esensi dari jurnalisme. Tanpa melakukan disiplin verifikasi, tidak mungkin jurnalis bisa mendapatkan informasi seakurat mungkin.
Saya akan ambil contoh, misal viral di media sosial, pada sebuah postingan, ditulis dosen Universitas A melecehkan mahasiswa ketika bimbingan skripsi. Ketika informasi postingan di sosial media itu sampai ke jurnalis, apakah lantas bisa ditulis.
Mungkin bisa, namun sumber informasinya tidak jelas, sebab kita tidak pernah tahu untuk kepentingan apa itu ditulis, dan siapa yang menulis. Maka langkah yang paling mudah adalah mengkonfirmasi langsung ke pihak rektorat. Karena bisanya akses ke korban cukup sulit, maka cara yang paling cepat adalah tanya ke pejabat kampus.
Langkah sederhana itu, cukup membuat jurnalis melakukan verifikasi. Ini membuat informasi yang disajikan semakin akurat. Apalagi setelahnya, jurnalis yang meliput berhasil mewawancarai korban dan pelaku atau orang-orang yang dekat dengan mereka, tentu informasi akan semakin mendekati realita.
Ini membuat saya teringat laporan dari Republika ketika meliput penjarahan para pejabat setelah rusuh pada September 2025 lalu. Jurnalis Republika berhasil berbincang atau wawancara dengan salah satu orang yang ketinggalan rombongan. Orang itu harusnya ikut rombongan untuk menjarah rumah salah satu pejabat Indonesia.
Dari laporan itu, publik bisa menentukan sikap dari kebenaran penjarahan itu. Ternyata yang melakukan adalah orang luar daerah, diangkut dengan mobil, dan dikoordinasi lewat grup WhatsApp. Apa yang dilakukan jurnalis dalam dua contoh itu, merupakan bagian dari disiplin verifikasi.
Namun jangan lupa, verifikasi dalam konteks tertentu harus juga memperhatikan prinsip keberimbangan. Meski saya pernah menulis esai yang mempertanyakan keberimbangan (klik di sini). Namun prinisp kebrimbangan ini tidak bisa ditinggalkan.
Misal, masih menggunakan kasus pelecehan di kampus, jurnalis tidak saja hanya meminta keterangan dari pihak korban, namun juga dari sisi pelaku. Palaku di sini bisa kuasa hukum, pihak kampus, dan keluarga terdekat. Prinsipnya memberikan ruang yang adil bagi dua belah pihak.
#Elemen Keempat: Independen
Independen tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan seorang jurnalis. Saya akan mencoba memulai dengan membedakan antara netral, objektif, dan independen. Kedua istilah ini sering disamakan. Meski ini bukan definisi final. Tapi batasan keduanya membantu untuk mempermudah mengpilkaskan independen di lapangan.
Netral berarti tidak memihak, tidak menentukan sikap, dan tidak mengambil posisi dalam satu peristiwa yang diliput. Lalu objektif adalah sikap wartawan yang menyajikan informasi sesuai fakta dengan melewati proses verifikasi.
Sedangkan, independen, sederhananya, tidak terpengaruh apapun untuk menentukan sikap demi kepentingan publik. Artinya jurnalis tidak dipengaruhi oleh pemilik media, pemodal, klein, dan lainnya.
Dari tiga hal itu, bagi saya, netral dan objektif adalah mitos belaka. Jurnalis tidak mungkin bisa netral karena pasti ia punya pandangan, idologi, dan nilai yang mempengaruhi sikapnya. Hal itu membuatnya tidak bisa netral. Contoh paling gampang, apakah ada kasus pembunuhan, jurnalis bisa netral tidak menaruh emosi ke perbuatan keji si pembunuh? Kalau empati kita masih ada, sepertinya sulit.
Begitu juga dengan objektivitas. Jurnalis tidak bisa objektif karena satu hal, keterbatasan menyajikan informasi secara utuh. Ia tidak mungkin bisa seratus persen bisa menangkap semua realita di lapangan dan menaruhnya dalam satu laporan utuh.
Jurnalis tetap manusia. Persis seperti lensa foto, ia hanya tidak bisa mengambil gambar melebihi frame. Jangkauannya terbatas. Soal ini, kalau ingin lebih detail, saya pernah menulis esai yang sempat saya singgung sebelumnya, Bias Keberimbangan (2020).
Maka penekanan saya di poin ini, adalah jurnalis setidaknya harus independen. Artinya ketika menyajikan informasi ia tidak terpengaruh oleh siapapun. Jurnalis harus independen sejak dalam pikiran. Setelah itu, jurnalis sebisa mungkin harus: independen dari narasumber, independen dari klien, independen dari perusahaan (pemodal/pemilik media), independen dari penguasa, dan seterusnya.
#Elemen Kelima: Monitoring Power and Offer Voice to the Voiceless
Ini berat, memantau kekuasaan (monitoring power), selalu berkaitan dengan memantau pemerintah, meski sebetulnya tidak selalu begitu. Namun ini dipertegas lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU itu, pers bahkan bisa dibilang sebagai pilar demokrasi apalagi dengan adanya pasal 2, 3, 6, dan 4 ayat 1.
Saya ambil contoh satu pasar, pada pasal 3, tertulis pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. “Kontrol sosial” di sini jelas bisa ditafsir bahwa jurnalis harus ikut mengawasi jalannya pemerintahan di berbagai level, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ada istilah untuk ini, yakni jurnalis sebagai anjing penjaga (watchdog). Meski akhir-akhir ini rasanya peran ini melemah.
Gambaran media sebagai kontrol kekuasaan atau pemerintah, bisa dilihat dalam film The Post (2017), Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House (2017), dan All the President’s Men (1976).
Namun kontrol sosial, termasuk memantau kekuasaan, tidak hanya sebatas mengawasi penguasa negara. Tapi juga siapapun yang berada di posisi dengan kuasa yang tinggi, misal otoritas agama. Misalnya Majalah Tempo dulu pernah mengungkap kejanggalan tata kelola lembaga filantropi semacam Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Kemudian kasus yang juga sering terungkap belakangan ini adalah kekerasan di lingkungan pondok pesantren yang melibatkan senior dan junior. Lebih parah, ada pencabulan yang dilakukan kiai atau ustad pondok terhadap santriwati. Fungsi media di bagian ini bisa dilihat dalam film Spotlight (2015).
Menyuarakan yang Tidak Bersuara
Meski poin ini tidak terlalu disinggung dalam bukunya Bill Kovach. Namun sejauh ini, pengalaman saya, tugas dari meja redaksi mengharuskan saya wawancara warga biasa. Biasanya ini disebut sebagai liputan grassroot. Ada kewajiban tidak tertulis, wartawan juga harus menjangkau kepentingan masyarakat paling bawah.
Misalnya, baru-baru ini Pemerintah di bawah Presiden Prabowo sedang menggencarkan Makan Bergizi Gratis. Jurnalis harus juga menjangkau penerima manfaat seperti sekolah, orang tua, dan siswa. Sehingga tidak terjebak hanya dari narasi pemerintah saja.
#Elemen Keenam: Journalism as a Public Forum
Saya ingin kembali pada 2020, ketika pandemi Covid-19 mulai masuk di Indonesia. Saya coba menggambarkan “jurnalisme sebagai forum publik” lewat pandemi, karena saya tidak menemukan contoh yang lebih baik.
Kalau kita perhatikan, waktu itu, diskusi publik tentang Covid-19 terbelah menjadi dua. Pertama, yang percaya Covid-19 secara ilmiah. Kedua, yang mempercayai Covid-19 dari kacamata konspirasi.
Seperti yang disinggung sebelumnya, tujuan jurnalisme adalah kebenaran fungsional. Maka, saya tidak akan protes ada media yang memfasilitasi orang-orang penganut konspirasi, meski sikap saya jelas tidak setuju. Namun sisi itu boleh saja dihadirkan untuk mengetahui mana yang benar dan salah.
Pers bisa berfungsi sebagai forum publik, untuk mendiskusikan antara dua hal yang mungkin berlawanan. Ini membantu warga atau publik terlibat dalam perdebatan yang lebih demokratis. Sehingga nantinya warga bisa menentukan sendiri sikapnya terhadap Covid-19.
Namun bukankah fungsi sebagai “forum publik” itu bisa dilakukan oleh influencer dan konten kreator lain. Iya betul, itu sangat mungkin. Namun yang paling ideal dan bertanggung jawab melakukan itu adalah jurnalisme, karena profesi ini terikat pada kode etik yang mengharuskan jurnalis mengabdi pada kebenaran dan kepentingan publik.
#Elemen Ketujuh: Menarik dan Relevan
Kerja jurnalis memang menghadirkan informasi yang penting. Tapi itu tidak cukup. Yang lebih sulit lagi adalah menghadirkan informasi yang penting, plus menarik, dan relevan. Tiga kombinasi ini butuh effort yang lebih.
Mari ambil contoh berita atau konten yang paling sangat disukai pembaca. Yang paling gampang menyebut entertainment, lebih spesifik lagi gosip. Gosip itu seperti sifat alami manusia. Bahkan tanpa media pun, orang-orang tetap akan mencari gosip dengan medium lain, misalnya di Pos Ronda dan penjual sayur.
Sementara jurnalis kadang suka mengeksploitasi aspek gosip ini karena lebih menarik dan mudah mendapat klik dari pembaca. Misalnya masalah personal pejabat publik, yang selingkuh. Atau bahkan hobi pejabat memelihara kucing. Alih-alih mengawasi dan menyajikan informasi terkait kebijakan si pejabat, jurnalis kadang terjebak di soal yang menarik tapi tidak penting.
Contoh lain jika ada kecelakan berulang di jalan. Biasanya kecelakaan berulang di jalan tol misalnya, dikaitkan dengan mistis. Sudut pandang liputan yang mistis ini mudah menarik pembaca, sebab alam pikir masyarakat kadang masih terjebak pada logika mistika.
Maka, jurnalis akan mudah sekali tergoda memberitakan bahwa jalan tol itu berhantu, sehingga banyak terjadi kecelakaan, ketimbang memberitakan penyebab teknis dari perspektif ahli.
Terkesan mudah diucapkan, tapi memang harus diakui, perlu pengalaman dan jam terbang untuk membuat informasi penting tetap relevan dan menarik untuk pembaca. Tapi salah satu yang paling ampuh, adalah dengan cara bercerita (story telling).
#Elemen Kedelapan: Berita Komprehensif dan Proporsional
KBBI menulis komprehensif dengan pengertian: (1) bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; (2) luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi).
Kalau ditarik dalam konteks jurnalisme, dari situ kita menangkap informasi yang tersaji dalam berita harus luas dan lengkap. Serta jurnalis di lapangan harus menangkap peristiwa atau objek liputan dengan baik.
Jurnalisme adalah kartografi modern. Ia menggambarkan sebuat peta warga bagi warga untuk mengambil keputusan tentang hidup mereka sendiri. — hlm. 210
Masalahnya, seperti yang sempat saya singgung di awal, mata kita terbatas. Sebanyak apapun data yang kita dapat di lapangan, sayangnya tidak semua bisa masuk. Tidak semua bisa disampaikan. Ada keterbatasan ruang, lebih lagi, ada bias dalam diri kita.
Di tengah perkembangan media di internet, kita sebetulnya sudah tidak punya batas untuk menulis berapa panjang. Termasuk membuat video untuk YouTube misal, videonya bisa berjam-jam. Namun psikologi orang hari ini, sudah tidak bisa lagi duduk lama untuk membaca dan menonton konten. Apalagi konten-konten serius nan berat.
Saya tidak punya tips jitu untuk membuat berita yang komprehensif. Menurut saya, ini adalah soal kepekaan. Maka satu-satunya cara adalah melatih kepekaan kita untuk menangkap apapun yang penting di lapangan, kemudian menyajikannya dengan cara paling efektif, menarik, dan relevan.
Proporsional
Proporsional dekat dengan keberimbang dan sebanding. Salah satunya soal memberi ruang yang berimbang ketika memberitakan konflik antara dua kubu. Sebetulnya ini juga sudah disinggung sebelumnya saat membahas verifikasi berita.
Namun perlu ditekankan kembali bahwa jurnalis harus menganggap narasumber setara. Setara juga berarti menganggap semua sama. Maka harus memberikan ruang yang sama pula, sekalipun itu penjahat, teroris, dan lainnya.
Dalam konteks yang lebih luas, proporsional juga berkaitan dengan konten. Jurnalis harus memandang sebagai manusia, bukan robot. Manusia punya rasa jenuh. Pembaca akan pening jika konten yang dimuat selalu isu-isu serius. Sesekali perlu ada intermezo, konten-konten ringan yang menghibur namun tetap perlu.
#Elemen Kesembilan: Hati Nurani
Saya akan berhenti di elemen kesembilan, dan tidak melanjutkan elemen ke sepuluh. Sebab buku yang saya pegang hanya sampai sini. Selain itu, setelah saya baca terbitan lebih baru, elemen kesepuluh sebenarnya juga sudah disinggung.
Bisa jadi, soal hati nurani ini adalah yang paling abstrak. Karena standar nurani setiap jurnalis akan berbeda.
Namun saya ingin menekankan satu hal, hati nurani setiap wartawan harus selalu dikaitkan dengan kebebasan berpendapat atau demokrasi.
Seperti sejarah awal jurnaslisme muncul. Jurnalisme sejak awal memang ada untuk kepentingan publik agar mereka tahu dan mengerti. Sehingga publik bisa bersuara dan bersikap. Tentu salah satunya dalam hal politik dan kebijakan pemerintah.
Selebihnya saya serahkan ke masing-masing personal.
Sebab pada akhirnya, soal hati nurani, itu berkaitan dengan nilai, moral, dan ideologi masing-masing wartawan. Gunakan itu untuk menilai sesuatu itu layak diberitakan atau tidak.